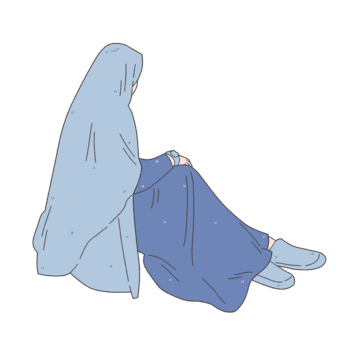Seorang perempuan perlahan berjalan di tepian jurang, samping
rumahnya. Mencoba memaksa ingatannya bekerja dengan baik, mengenang tentang
sesuatu yang meresahkan, sesuatu tentang peristiwa silam, beberapa tahun ke
belakang dari tempatnya terdiam sekarang.
Ada sesuatu yang hilang, entah. Bahkan ia tak merasa
kehilangan apa-apa. Ada sesuatu lain yang menurut akal sehatnya harus ia
miliki, tapi kemudian ia lepaskan. Tapi
apa? Karena nyatanya ia memiliki apa-apa yang ia punya.
Perempuan, kembali memaksa otaknya bekerja lebih keras
lagi. Sial, ingatannya memang payah, separah itukah? Sepuluh tahun yang lalu?
Ah, tidak. Dua, tiga puluh tahun yang lalu. Dan sekarang nyatanya perempuan
baik-baik saja. Jika menurutmu baik adalah bahwa perempuan itu kini tak terbaring
sakit, anggap saja memang itu artinya ‘baik’.
Perempuan beranjak ke lain tempat, tidak lagi di tepi jurang
sisi kanan rumah tinggi bercat putih keabu-abuan. Sekarang lebih memilih duduk
di tepi kolam buatan, dan masih tetap berpikir dan mengingat-ingat apa gerangan
yang sebenarnya ia lupakan.
Sayup terdengar suara sepasang anak remaja, oh bukan
sepasang ternyata ia sendirian, tertawa cekakan di ujung telpon yang ia
genggam. Perempuan meliriknya “Hi, oma” remaja tertawa renyah. Ah, iya aku
ternyata seorang nenek tua yang sedang duduk di pinggir kolam. Airnya mencetak
bayangan wajah yang tak tampak kerutan, ternyata perempuan belum terlalu tua
untuk disebut nenek tua. Tapi kenapa ingatannya begitu lemah. Tak mampu
mengingat sesuatu yang rasa-rasanya harus diingat.
Gerimis kecil, airnya jatuh satu satu membentuk
bulatan-bulatan di air kolam. Perempuan beranjak masuk dan merebahkan diri di
kursi panjang ruang tengah. Remaja yang memanggil “Hi, oma” barusan masih
tertawa dan berbicara dengan suara sedikit dipelankan, namun telinga perempuan
rupanya masih bisa mendengar dengan jelas “Udah dulu yaa sayang”. Ah, perempuan
terkejut, tiba-tiba matanya membulat, membetulkan letak kaca mata dan bersegera
berjalan ke kamar.
“Sayang” aku pernah sangat hafal mengucapkan itu persis
seperti remaja tadi. Tapi pada siapa, rasanya perempuan masih memerlukan
kata-kata lain untuk mengingatnya. Mungkin sebuah nama, “kekasih”. Perempuan
mengingat pria yang terakhir ia sebut kekasih, ia masih hidup dan sehat-sehat
saja. Bahkan ia sudah memberikannya tiga anak dan empat cucu lucu seperti
impiannya dulu. Termasuk remaja yang baru saja duduk tak jauh dengannya tadi di
ruang tamu.
Perempuan terduduk di sisi tempat tidur, aku memiliki
kekasih, kekasih lain, bukan dia, bukan pria itu. Kekasihku, oh kekasihku. Air
mata perempuan berusia 50 tahun tak terasa jatuh satu satu. Dua, tiga puluh
tahun yang lalu. Perempuan berhasil ingat kekasihnya yang hilang dulu, bukan
hilang tapi lebih tepatnya ia tinggalkan. Kekasih yang lebih tulus, lebih baik,
lebih mencintainya dan lebih mengerti akan apapun yang perempuan mau. Dia,
sesuatu yang hilang itu, perempuan tersedu. Mengingat semuanya dengan jelas
bayangan dua, tiga puluh tahun yang lalu.
Kekasihku oh kekasihku, mungkin aku bukanlah aku yang sekarang
andai dulu memutuskan hidup bersama denganmu.
*Ijinkan ku berandai
“perempuan itu” adalah aku, dua tiga puluh tahun kemudian, aku yang ternyata
tak bisa menghabiskan sisa hidupku berdampingan denganmu, kekasihku.