Sebagai rakyat kecil, aku ingin tetap menyuarakan rasa syukur atas berdirinya kota 'kebanggaan' yang sudah mencapai usia ke 484 ini.
Usia yang sudah tak lagi muda. Sesuai dengan umur yang semakin bertambah, sepertinya kelelahan semakin menggantung di kelopak mata kota besar ini. Terengah-engah mengimbangi teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin menggila setiap hari. Namun, mereka sama sekali tak peduli usia kota yang semakin renta. Yang mereka tau, semua kegiatan tetap berjalan di atas roda yang menggilas punggung kota dengan nyaman dan senyum kebanggaan. Jerit hati kecil sang kota tua tak lagi didengar dan dipedulikan. Bahkan di hari ulang tahunnya yang kebetulan hari ini menginjak angka 484, semua warga berpesta merayakan kesenangannya masing-masing dengan cara mereka, walau tetap dengan judul “Happy 484th Anniversary for Jakarta” akan tetapi adakah yang peduli pada isak tangisnya. Setiap hari ia menyaksikan pertumbuhan perekonomian, kemodernan teknologi, kemajuan cara manusia berpikir, ulah para remaja yang kadang tak terkontrol, termasuk kelakuan sang intelek dan terpelajar yang kebanyakan masih berhati dan bermulut ‘kotor’. Semua itu ia rekam dalam memori pahit yang senantiasa menjadi kenangan. Resiko menjadi sebuah ibu dari semua kota di salah satu kepulauan asia tenggara di belahan bumi ini. Resiko yang tak mungkin ia tolak keangkuhan sikapnya, keegoisan hati yang berpijak di tanahnya, serta kekejaman yang senantiasa membayangi kebesaran namanya.
Aku, Aisyah Ayya Az Zahir.. mengucapkan “selamat ulang tahun” kotaku, Jakarta, aku peduli padamu.
Kota tua menjerit, meronta, mengharap kesucian dari apa yang pernah ia lihat, pernah ia rasakan. Kota ini menjadi sejarah kebejatan para orang yang tak bertanggung jawab. Darah berceceran di atas aspal dari kebiadaban manusia yang haus akan harta yang ia rampas dari manusia lain. Di sudut yang lain, bayi tak berdosa tergolek tanpa ada wanita yang mengaku bahwa ia keluar dari rahimnya. Potongan-potongan tubuh manusia yang sejatinya adalah makhluk sempurna tergeletak tanpa identitas. Tangan-tangan mungil dengan sebuah benda sebagai pengiring nyanyian yang keluar dri mulut mereka bergelantungan di angkutan2 yang menyeret nasib hidupnya berada di jantung kota tua ini. Punggung-punggung renta berbalut kain lusuh tergolek lemas di ujung jembatan dengan cawan berisi receh hasil belas kasihan orang yang berlalu lalang. Mata tajam dengan sebilah pisau di pinggang senantiasa bergentayangan di bis kota membayangi langkah-langkah wanita dengan dekapan tas di dada. Ceracau mulut yang tak jarang mengeluarkan isi kotak sampah dan kebun binatang tumpah di jalanan. Wanita-wanita yang secara terpaksa berdiri berjam-jam dipinggiran jalan mengharap ada kendaraan yang berhenti dan membawanya pergi, dan pulang dengan beberapa lembar uang untuk memberi anaknya makan. Antrean panjang mobil dan motor berharga triliunan berlalu lalang memenuhi ruas jalan tiap detiknya, tanpa henti. Asap-asap pabrik mengepul pertanda hidupnya produksi yang kian hari kian bersaing menghidupi pekerja-pekerja yang berseragam keluar dengan gaji yang pas-pasan. Pejalan kaki, anak tak beralas kaki, wanita bermake up tebal dan berhak tinggi, melangkah menyusuri trotoar bahu jalanan berlobang dihiasi pedagang-pedagang yang membentangkan terpal penutup hujan, tak jarang sumpah serapah terlontar dari para pengendara mobil mewah.
Gedung-gedung mewah pencakar angkasa berisi manusia-manusia intelek yang disibukan dengan setumpuk pekerjaannya, dasi dan jas rapi mewarnai hari-harinya, sepatu mengkilat seolah tak boleh ada noda sedikitpun yang menempel karna bersihnya. Wajah-wajah yang hilir mudik bertegger wajahnya di layar kaca televisi. Beradu argumentasi merasa diantara mereka, dia lah yang paling benar, bahkan lebih benar dari pada Tuhan. Berusaha mendapatkan kursi-kursi kekuasaan. Berebut harta tak ubahnya anjing-anjing kelaparan yang dilempar setumpuk tulang sebagai pakan, saling sikut, saling tendang, ingin mendapat yang paling banyak. Mereka sama memiliki mata dan hati. Mata dan hati yang kadang mereka tak bisa membedakan cara memfungsikannya, atau bahkan tak berfungsi sama sekali. Ucapan-ucapan manis acapkali keluar dari bibirnya. Membodohi rakyat kecil yang memang bodoh berada di negeri ini.
Mereka, sang cendekiawan, mengertikah akan jerit tangis sang pengamen jalanan yang tiga hari tiga malam tidak makan. Mereka sang ibu muda yang membuang bayi tak berdosa, pahamkah akibat dari apa yang telah kalian lakukan. Mereka, sang pengemis tua, dimanakah saudara-saudara kalian berada.
Kota tua menangis. Hingga kini, di usianya yang ke 484, ia meminta butakan saja matanya, bekukan sudah hatinya, patahkan tulang punggungnya, lumpuhkan kakinya, kunci mulutnya rapat-rapat. Ia tak sanggup melihat kehidupan liar manusia-manusia yang berpijak ditanahnya. Ia tak ingin semakin tercabik-cabik hatinya oleh perasaan bersalah membiarkan mereka berulah mengotori tubuhnya dengan sampah. Ia sudah lelah dan tak kuat menanggung beban yang selama ini di usungnya. Ia tak mampu lagi berjalan mengimbangi laju globalisasi yang semakin menghilangkan etika, agama, dan estetika. Ia enggan berkomentar apa-apa, bungkam dengan air mata menggenang.
Tiada keramahan, tiada keindahan, tiada kasih sayang, tiada ketenangan, dan ketentraman. Berharap masih ada tangan yang mempedulikan rindunya akan kedamaian hati dan keteduhan jiwa. Jiwa sang kota tua yang terperangkap dalam gemerlap dunia.

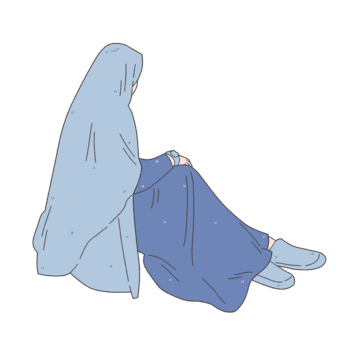









2 Comments
inilah kehidupan yang sebenarnya, tidak hanya di kota Djakarta saja, namun beruntung masih ada kota yang tidak separah Djakarta yaitu Daerah....
BalasHapus:)
Bogor doonnnggg :p
BalasHapusSilahkan tinggalkan pesan di sini: