Kusudahi doa malam ini, kuseka perlahan sisa air mata yang mengalir dipipiku. Ritual malam, hoby, kebiasaan, atau sebut saja sebuah rutinitas, bahkan aku merasa para malaikat-malaikat yang senantiasa setia menemani hari-harikupun sudah hapal dengan kebiasaanku, hapal susunannya, terjaga dikeheningan malam_disaat orang lain terlelap, mengambil air wudhu, sholat beberapa rakaat, lantas kemudian berdoa dan terisak hingga berjam-jam, merekapun hapal permintaan dan kata-kata yang saking seringnya kuucapkan setiap malam dengan tanpa melihat dan mencatat entah amal baik atau amal buruk. Aku tak peduli siapa yang akan mencatatnya, Roqib atau Atid..?? yang penting aku sudah memohon dengan ikhlas tanpa minta imbalan apapun, tanpa pernah ada niatan sedikitpun untuk ingin tahu mereka mencatat amal perbuatanku atau tidak. Dan seperti biasa, beban hidup yang aku tanggung selama 27 tahun sedikit berkurang, mungkin sekitar 0,27%.
Aku berjalan mendekati pembaringan, mencicikan air minum dan lantas meneguknya sedikit demi sedikit. Terlihat jam duduk di tas meja kamarku menunjukan pukul 05.00 pagi, namun tak ada sedikitpun cahaya masuk ke dalam jendela kamarku yang memang se ngaja kututup dengan kain gelap. Aku enggan melihat dunia, aku benci menatap mentari pagi yang baru terbit menyinari permukaan bumi. Aku muak dengan semua itu.
ngaja kututup dengan kain gelap. Aku enggan melihat dunia, aku benci menatap mentari pagi yang baru terbit menyinari permukaan bumi. Aku muak dengan semua itu.
 ngaja kututup dengan kain gelap. Aku enggan melihat dunia, aku benci menatap mentari pagi yang baru terbit menyinari permukaan bumi. Aku muak dengan semua itu.
ngaja kututup dengan kain gelap. Aku enggan melihat dunia, aku benci menatap mentari pagi yang baru terbit menyinari permukaan bumi. Aku muak dengan semua itu.
Cukup lama aku menghabiskan sisa waktuku di villa ini, mengurung diri, mendekatkan hatiku padaNya, pada Alloh, Tuhan yang baru saja aku kenal, yang namaNya baru saja sering ku sebut akhir-akhir ini, selama tiga tahun terakhir ini.
Waktu menunjukkan pukul empat sore, perlahan aku berjalan keluar menapaki jalan bebatuan di depan villa. Kuhirup udara pegunungan yang sedikit meringankan sesak dadaku. Seperti biasa, duduk disebuah kursi kayu tua yang menghadap ke arah perbukitan di bawah sana, pemandangan yang tak dapat terlukiskan keindahannya, aku bisa menatap langsung sebuah kawah putih yang nampak seperti mulut mengang a seolah bumi sedang menguap yang terletak di lereng gunung Patuha, dihiasi pepohonan lengkap dengan suara-suara hewan hutan liar yang tak pernah terjamah. Perlahan daun pohon-pohon yang menjulang itu melambai, seakan memberi senyum kearahku, atau mungkin mereka malah mengejekku..? aku tertunduk, tiba-tiba aku merasa dadaku sakit melihat daun-daun itu. Aku merasa pepohonanpun seakan tak ingin melihatku menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Tuhan mereka. Aku memejamkan mataku, menahan getir yang sangat pahit aku telan. Aku benci dengan hidupku, aku benci diriku.
a seolah bumi sedang menguap yang terletak di lereng gunung Patuha, dihiasi pepohonan lengkap dengan suara-suara hewan hutan liar yang tak pernah terjamah. Perlahan daun pohon-pohon yang menjulang itu melambai, seakan memberi senyum kearahku, atau mungkin mereka malah mengejekku..? aku tertunduk, tiba-tiba aku merasa dadaku sakit melihat daun-daun itu. Aku merasa pepohonanpun seakan tak ingin melihatku menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Tuhan mereka. Aku memejamkan mataku, menahan getir yang sangat pahit aku telan. Aku benci dengan hidupku, aku benci diriku.
 a seolah bumi sedang menguap yang terletak di lereng gunung Patuha, dihiasi pepohonan lengkap dengan suara-suara hewan hutan liar yang tak pernah terjamah. Perlahan daun pohon-pohon yang menjulang itu melambai, seakan memberi senyum kearahku, atau mungkin mereka malah mengejekku..? aku tertunduk, tiba-tiba aku merasa dadaku sakit melihat daun-daun itu. Aku merasa pepohonanpun seakan tak ingin melihatku menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Tuhan mereka. Aku memejamkan mataku, menahan getir yang sangat pahit aku telan. Aku benci dengan hidupku, aku benci diriku.
a seolah bumi sedang menguap yang terletak di lereng gunung Patuha, dihiasi pepohonan lengkap dengan suara-suara hewan hutan liar yang tak pernah terjamah. Perlahan daun pohon-pohon yang menjulang itu melambai, seakan memberi senyum kearahku, atau mungkin mereka malah mengejekku..? aku tertunduk, tiba-tiba aku merasa dadaku sakit melihat daun-daun itu. Aku merasa pepohonanpun seakan tak ingin melihatku menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Tuhan mereka. Aku memejamkan mataku, menahan getir yang sangat pahit aku telan. Aku benci dengan hidupku, aku benci diriku.
Malam ini, seperti hari-hariku yang sebelumnya. Tiga jam ritual doa kulantunkan untuk_Nya, hingga fajar menyingsing, membuka pagi dan hari yang baru. Aku mulai menutup buku catatan harianku dan merapikannya di kotak dalam lemari. Aku terbaring di tempat tidur, menatap atap langit-langit kamarku. Perlahan mataku terpejam, sementara jari jemari tanganku saling menggenggam erat di atas dada yang mulai sesak. Dan, akupun terlelap.
Paris, 1979
Suasana club tidak seperti biasanya, malam ini terasa agak sepi, mungkin sebagian pria-pria hidung belang itu mulai dikurung dan dipenjara olah istrinya masing-masing di rumah, atau mungkin uang mereka habis untuk biaya berobat ke rumah sakit karena Syphilis yang mereka derita tak juga kungung sembuh. Entahlah, aku tak peduli, aku kembali meneguk Sanwaiejk* (red wine 92’) ku yang hampir habis setengahnya, jari manisku membuang puntung rokok yang entah untuk kesekian batang.
“It’s so desolated, isn’t it?
“Hmmm,,,”
Aku hanya bergumam, menanggapi keluhan pimp (germo) ku yang berbibir merah itu. Aku bisa memastikan bibirnya semerah apa, dan wajahnya sepucat apa dengan tanpa melihat jelas di bawah lampu yang cahayanya seakan hanya berkekuatan 2,5 watt yang sudah setengah abad tidak diganti bohlamnya.
“Are you Ok..?”
Tampaknya Nyonya Monicca tak tahan melihat gelagatku yang sedari tadi hanya duduk terdiam menghabiskan berbotol-botol minuman dan beberapa bungkus rokok, dengan tanpa bicara apa-apa.
Aku mengangguk. Sejenak aku menatapnya, wanita separuh baya yang usianya sekitar 45 tahunan namun masih sangat tak tahu malu menggunakan pakaian yang hampir membuka sekujur tubuhnya itu, menatap mata yang bulatan putihnya sudah tak lagi putih, entah karena oleh asap rokok yang mengotori kelopak matanya atau karena tertekan oleh keadaan yang menghimpitnya, penderitaan yang sudah bertahun-tahun dirasakan, sama sepertiku . Bedanya, Monicca memang sudah terlahir dan mungkin akan mati di tempat ini. Di sebuah klub malam di kota Sainte-Anne, sebuah kota yang terletak di bagian tengah selatan pulau Martinigue di Laut Karibia.
. Bedanya, Monicca memang sudah terlahir dan mungkin akan mati di tempat ini. Di sebuah klub malam di kota Sainte-Anne, sebuah kota yang terletak di bagian tengah selatan pulau Martinigue di Laut Karibia.
 . Bedanya, Monicca memang sudah terlahir dan mungkin akan mati di tempat ini. Di sebuah klub malam di kota Sainte-Anne, sebuah kota yang terletak di bagian tengah selatan pulau Martinigue di Laut Karibia.
. Bedanya, Monicca memang sudah terlahir dan mungkin akan mati di tempat ini. Di sebuah klub malam di kota Sainte-Anne, sebuah kota yang terletak di bagian tengah selatan pulau Martinigue di Laut Karibia.
Aku mengenal Monica sejak berusia 9 tahun, seorang pria tua yang membawaku ke tempat ini, pria yang menjadi tetangga rumahku di desa Saint-Benoit-du-Sault, sebuah desa yang terletak sekitar 20 km barat daya Argenton-sur-Creuse di pusat Prancis. Rupanya ibuku mempunyai banyak hutang pada pria tua yang akhirnya mengenalkanku pada Monica, menjadikan aku sebagai budaknya, hingga aku menjadi wanita penghibur seperti dia. Sebenarnya keadaan ibuku pun tak jauh beda dengan Monica. Patricia Kaas, ibuku bahkan lebih tersohor dibanding Monica, seorang pelacur kelas kakap yang akhirnya mati karena AIDS. Dan Evaldo Kaas, seorang pria yang sering disebut-sebut ibuku hingga meninggalnya, menurutnya pria yang sejak aku lahir belum pernah kulihat wujudnya itu adalah ayahku,, ha ha ha mungkinkah seorang anak pelacur bisa memastikan salah satu pria sebagai ayahnya. Aku tak pernah peduli, yang aku tahu bahwa saat ini aku bisa menghasilkan uang banyak dari hasil belaianku setiap malam untuk para pria hidung belang.
Dari arah pintu masuk, tampak seorang pria tampan, berusia sekitar 25 tahun, saat itu usiaku sekitar 19 tahun. Dengan tampilan sederhana dan langkah pelan, ia berjalan memasuki pub menoleh ke kiri dan ke kanan, memberi senyuman pada wanita-wanita muda yang mulai berdatangan merayunya. Perlahan duduk disebuah kursi, tapi tidak memesan minuman, terlihat ia menolak tawaran seorang bar tender yang asyik membolak-balikan botol minuman dengan lihainya. Dia hanya memandang sekeliling layaknya perampok yang mengincar sebuah Bank, dan berharap sepi. Aku memperhatikan dari jauh ia mengeluarkan sebatang rokok dan pemantik dari saku kemejanya, lantas menyulut dan menghisapnya. Ia mulai bertanya-tanya pada seseorang yang sepertinya pelanggan tetap club ini, seorang lelaki paruh baya yang kesadarannya hampir hilang karena minuman yang dia teguk.
Perlahan, aku mendekat, menyapanya dengan gaya seorang pelacur kelas tinggi, bukan merayu, tapi lebih kepada menawarkan, menawarkan bantuan atau informasi yang mungkin bisa membantunya. Untuk apa seorang pria muda tampan datang ke tempat seperti ini kalau tidak untuk minum atau mencari wanita nakal. Tapi sepertinya tidak, bukan itu yang ia cari. Dia tersenyum kearahku, senyum yang sungguh tak dapat kulukiskan keindahnnya, tatapan mata yang bersih dan senyum yang sangat ikhlas seolah keluar dari hati yang teramat suci dan tersungging dari bibir yang seakan tak pernah tersentuh noda. Berbeda dengan tatapan nakal pria hidung belang dan senyuman liar serta gerakan-gerakan lincah tangan kasar laki-laki yang tampak sekali kebejatannya. Ia mengulurkan tangannya sambil terus menatapku. Aku seakan tak sanggup menatap kedua mata pria itu, aku alihkan pandanganku ke sekeliling, seraya menghembuskan asap rokok dari bibir merahku. Akupun menjabat tangannya, sesaat.
“Bryan”
“Maggie”
Tak ada yang special, perkenalanku sangat singkat, tapi aku tak bisa melupakannya. Dia tidak berbuat apa-apa, tidak meminta apa-apa, ia hanya mengajakku ngobrol, obrolan tak tentu arah, tapi sangat berkesan. Pertama aku merasa sangat tidak nyaman karena aku membuka percakapan dengan langsung menawarkan diri, tapi rupanya Bryan sangat memaklumi dan memahami pekerjaanku. Dia menolak dengan bahasa yang seperti seorang pangeran membujuk sang puteri untuk menghibur kesusahan hatinya. Kami larut dalam obrolan yang lumayan panjang, hingga ia pergi meninggalkan “istana”ku. Setelah itu aku tak pernah lagi bertemu dengan Bryan, laki-laki tampan yang tutur bahasa dan sikapnya sangat mempesona. Hidung mancung dihisi bekas cukuran kumis dan brewok kasarnya di pipi selalu menghiasi pelupuk mataku. Aku mulai selalu membayangkannya. Ugh, perlahan aku tersadar, tak pantas seorang pelacur jatuh cinta. Tak mungkin.
Tapi sungguh, aku benar-benar terpikat oleh pesona Bryan, pria yang hanya kurang lebih 2 jam menemani hidupku. Aku mulai tak konsentrasi dengan pekerjaanku, tak bisa segenit biasa ketika menemani tamu-tamu yang membawa uang beribu-ribu dolar yang bisa kudapatkan dalam semalam. Bryan tak pernah memberiku uang, bahkan tak menyentuhku sedikitpun selain berjabat tangan. Ia sekalipun tak memuji kecantikan wajahku seperti yang selalu diucapkan pria-pria itu ketika pertama kali melihatku. Aku adalah pelacur tercantik di klub ini, bahkan mungkin di kota ini. Tapi sepertinya itupun luput dari pandangan Bryan. Dia memandangku tanpa binar kekaguman sama sekali. Aneh.
Selain itu, pesona yang ia hadirkan tak hanya ketampanan wajahnya dan tinggi kekar badannya, namun lebih dari itu, yaitu tutur lembutnya dan bagaimana ia menghormati seorang wanita kotor sepertiku. Dan satu pertanyaannya, yang hingga sampai saat ini masih kuingat dan sempat menghujam jantungku.
“Did you have aim to come out from here?”
Aku tak menjawabnya, tapi dadaku sesak. Apa yang ia inginkan? Bukan diriku, bukan tubuhku, tapi apa?? aku tak sempat bertanya karena tiba-tiba telpon selularnya berbunyi.
“I’m Sorry” ia tersenyum ke arahku, aku hanya tersenyum masam kemudian menatap keseliling pub yang mulai sepi.
“Assalammualaykum... yeah,, !! oh, maaf, aku masih di Paris. Secepatnya aku kirim, besok pagi aku pulang dan langsung ke Bandung,, Ok, terima kasih. Waalaykummsalam.”
Nit.
Ia mematikan teleponnya, dan kembali menatapku.
“Meggie, I’m so consoled to talk to you. And I hope you don’t have a feel offended for my last word. This is our first meet, but I sense like too the most often. I must come back to my home,,, mmmm exactly to my town, Indonesia, thanks for your time, see you”
Secepat itu, tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab bahkan mengangguk, ia pun lupa menjabat tanganku. Tergesa-gesa ia pergi berlalu dari hadapanku, meninggalkanku yang terperangah menatap kepergiannya.
Kaki putihku yang jenjang menapaki hamparan pasir putih sepanjang laut ini. Sainte-anne memang sebuah kota yang dikelilingi laut yang indah, daerah pantai yang bersih dan sangat panjang dengan dihiasi pasir sedivymnya yang terkenal sangat putih dan bersih. Namun yang selalu menjadi tujuan utama pengunjung adalah karang pantai yang indah, banyak penyelam sengaja mendatangi kawasan ini untuk berwisata ke bawah laut yang terdapat taman Aguascope.
Perlu kuberitahu, aku sudah tak lagi bekerja di klub malam, aku tak pernah bertemu dengan pria hidung belang, sejak Monica meninggal karena AIDS, penyakit yang wajib diidap oleh semua pelacur sepertiku. Dengan sisa uang hasil “jerih payahku” memeras keringat najis yang keluar dari tiap pori-pori kulitku, aku mulai menyusun rencana untuk meninggalkan kota kecilku. Aku akan meninggalkan Paris. Tekadku sudah bulat.
Indonesia, 1983
Aku mendarat di bandara Husein Sastranegara, Bandung. Setelah sebelumnya aku terbang dari Singapura. Aku tak mengenal Indonesia, tapi aku mengenal Bandung, kota yang pernah kudengar satu kali seumur hidupku. Dari mulut Bryan. Yah, beberapa bulan setelah itu tiba-tiba hatiku berontak ingin keluar dari kehidupan hitam yang menghimpitku. Bahkan aku mulai membangkang pada Nyonya Monica, wanita yang selama ini memberiku segalanya. Memberiku kehidupan dan materi yang melimpah, hingga hidupku mewah. Bertahun-tahun aku tak pernah sedikitpun punyai niatan untuk lari dari kehidupanku, aku sungguh menikmatinya, menikmati hidup dikelilingi oleh berbagai macam pria yang kupikir hanyalah binatang berwujud manusia. Tapi sejak pertama kali bertemu Bryan, aku mulai berubah, dan memutar siklus kehidupanku. Aku mulai berani membayangkan seandainya Bryan jadi suamiku, aku akan tinggal di negara asing yang ia sebut Indonesia, persetan di mana saja aku akan tinggal, yang jelas aku ingin sekali merasakan hidup berumah tangga dan dengan Bryan. Meninggalkan kehidupan lamaku. Punya keluarga dan anak anak-anak yang lucu, hmm, Mungkinkah. Satu-satunya cara adalah aku harus pergi ke Indonesia. Selepas kepergianku meninggalkan Paris, aku memutuskan untuk pergi ke Bandung.
Sungguh, aku menemukan kehidupan seperti bukan layaknya di dunia nyata, aku merasa bahwa aku bukanlah Maggie Kaas, seorang pelacur kelas tinggi yang harganya mahal dan dicintai banyak pria, namun dihujat banyak orang, dipandang seperti hewan oleh sebagian makhluk yang mengaku mereka suci, kemanapun aku melangkah keluar pub, anjing kudisan saja seakan meludahi wajahku. Tapi aku sudah kebal dengan semua itu, aku merasa di manapun aku tinggal keadaannya akan tetap sama, termasuk di Bandung, Indonesia. Tapi tekadku untuk menemukan kota ini begitu kuat, entah karena aku ingin mencari Bryan, atau karena aku ingin mencoba mencari udara baru dalam hidupku. Dan aku siap menerima perlakuan apapun di kota baru ini. Dilempari, diludahi, atau bahkan dijadikan bahan ejekan layaknya orang gila borokkan dipinggir jalan.
Aku kecele, pertama kali menginjakkan kaki di kota ini, semua pikiran-pikiran buruk yang selama ini jadi bayanganku sirna terhapus senyum ramah penduduk kota ini. Aku terperangah, takjub. Mungkin karena mereka tidak kenal siapa aku, sampah busuk dari sebuah pulau di kota romantis Paris. Aku tidak mengerti bahasa mereka, aku juga tidak kenal mereka, tapi aku mencoba membalas senyum seramah mereka, senyum yang mungkin baru pertama kali kusunggingkan untuk orang lain dengan ikhlas. Aku berjalan ke arah utara, ke tempat Tourist Information Center. Dari sana aku bisa mendapatkan informasi seputar kota ini. Aku memutuskan menginap di hotel Preanger, hotel yang pertama dibangun pada tahun 1889 dan diperbaharui pada tahun 1928 oleh seorang arsitek terkenal bernama Wolf Schoemaker. Hotel ini memiliki sudut-sudut yang tajam (Blocky Style) mirip dengan arsitektur dari bangsa Maya di Meksiko. Hotel ini bersebrangan dengan Hotel Savoy Homann dari sebelah utara pertigaan jalan Asia-Afrika dan jalan Tamblong.
Aku kecele, pertama kali menginjakkan kaki di kota ini, semua pikiran-pikiran buruk yang selama ini jadi bayanganku sirna terhapus senyum ramah penduduk kota ini. Aku terperangah, takjub. Mungkin karena mereka tidak kenal siapa aku, sampah busuk dari sebuah pulau di kota romantis Paris. Aku tidak mengerti bahasa mereka, aku juga tidak kenal mereka, tapi aku mencoba membalas senyum seramah mereka, senyum yang mungkin baru pertama kali kusunggingkan untuk orang lain dengan ikhlas. Aku berjalan ke arah utara, ke tempat Tourist Information Center. Dari sana aku bisa mendapatkan informasi seputar kota ini. Aku memutuskan menginap di hotel Preanger, hotel yang pertama dibangun pada tahun 1889 dan diperbaharui pada tahun 1928 oleh seorang arsitek terkenal bernama Wolf Schoemaker. Hotel ini memiliki sudut-sudut yang tajam (Blocky Style) mirip dengan arsitektur dari bangsa Maya di Meksiko. Hotel ini bersebrangan dengan Hotel Savoy Homann dari sebelah utara pertigaan jalan Asia-Afrika dan jalan Tamblong.
Aku merebahkan penat tubuhku di atas ranjang yang empuk, aroma udara sejuk memasuki rongga dadakku.
Aku terbangun ketika ada suara yang sangat asing ditelingaku, seperti suara orang  bernyanyi atau memanggil seseorang dengan pengeras suara. Kutajamkan pendengaranku, mengira-ngira suara apa itu. Perlahan aku bangun, dan berjalan ke arah balkon kamar hotel, membuka pintu dan menghirup udara yang sunguh sangat segar. Aku menatap sekeliling, jam menunjukkan pukul 04.30 pagi, tapi kehidupan di kota ini sudah mulai tampak. Berbanding terbalik dengan kehidupanku, yang justru jam segini mulai menutup mata dan melepas penat setelah semalaman begadang dan mencari uang.
bernyanyi atau memanggil seseorang dengan pengeras suara. Kutajamkan pendengaranku, mengira-ngira suara apa itu. Perlahan aku bangun, dan berjalan ke arah balkon kamar hotel, membuka pintu dan menghirup udara yang sunguh sangat segar. Aku menatap sekeliling, jam menunjukkan pukul 04.30 pagi, tapi kehidupan di kota ini sudah mulai tampak. Berbanding terbalik dengan kehidupanku, yang justru jam segini mulai menutup mata dan melepas penat setelah semalaman begadang dan mencari uang.
 bernyanyi atau memanggil seseorang dengan pengeras suara. Kutajamkan pendengaranku, mengira-ngira suara apa itu. Perlahan aku bangun, dan berjalan ke arah balkon kamar hotel, membuka pintu dan menghirup udara yang sunguh sangat segar. Aku menatap sekeliling, jam menunjukkan pukul 04.30 pagi, tapi kehidupan di kota ini sudah mulai tampak. Berbanding terbalik dengan kehidupanku, yang justru jam segini mulai menutup mata dan melepas penat setelah semalaman begadang dan mencari uang.
bernyanyi atau memanggil seseorang dengan pengeras suara. Kutajamkan pendengaranku, mengira-ngira suara apa itu. Perlahan aku bangun, dan berjalan ke arah balkon kamar hotel, membuka pintu dan menghirup udara yang sunguh sangat segar. Aku menatap sekeliling, jam menunjukkan pukul 04.30 pagi, tapi kehidupan di kota ini sudah mulai tampak. Berbanding terbalik dengan kehidupanku, yang justru jam segini mulai menutup mata dan melepas penat setelah semalaman begadang dan mencari uang.
Tampak di bawah tempatku berdiri, segerombolan wanita dengan pakaian serba putih menenteng sesuatu seperti kain menuju ke arah gedung yang kupikir dari situ suara asing tadi terdengar. Aku memperhatikan langkah mereka memasuki gedung putih yang berkubah itu. Aku kembali masuk, kehidupan yang benar-benar sangat asing bagiku. Air pagi ini begitu sejuk membasuh tubuhku yang mulus. Selepas mandi dan sarapan aku keluar hotel dan berjalan ke arah barat, melewati tempat-tempat makan hingga bioskop dan pasar. Aku terus berjalan menyusuri pinggiran kota. Sesekali membalas senyum ramah penduduk ini, walau aku tak mengerti apa yang mereka ucapkan. Kesan pertamaku di kota Bandung, kota dengan penduduk yang sangat ramah. Dan aku menikmatinya.
Bandung, 1985
Ternyata sudah dua tahun, aku tinggal di kota ini. Bandung. Aku tidak pernah kenal kota Indonesia lain selain Bandung, hingga kini aku tak kenal Indonesia. Tapi aku mulai menguasai bahasanya, aku mendapat keluarga baru yang sangat baik, keluarga bapak Abdulrahman dan ibu Asyifa, serta seorang putri tunggalnya Aisyah. Keluarga yang sudah mengajarkan berbagai macam hal, mulai dari kebudayaan, daerah, kota wisata, makanan, cara bersosialisasi dan bersikap layaknya wanita santun. Dan lebih dari itu, aku mendapatkan sesuatu yang lain yaitu, tentang islam. Agama yang sangat sangat indah. Mereka dengan telaten mengajarkanku tentang Adam dan Hawa, tentang Rasululloh SAW lengkap dengan kehidupannya, kesehariannya, mengajarkan bahwa betapa Alloh, Tuhan mereka Maha pengampun, Maha Melihat dari sesuatu zat yang tak terlihat, Maha menguasai dari segala bentuk apapun yang tak terjangkau. Aku terperangah, membatu. Mungkinkah Ia, mau jadi Tuhanku...??? jika Ia tahu bahwa aku hanyalah seonggok najis yang hewanpun enggan menyentuhnya. Tapi, apa betul kata bapak tadi kalau Ia Maha Melihat dan Maha Pengampun? Ah, aku tak yakin..
Tapi beberapa tahun ini, mereka tak pernah lelah mengajariku, aku pusing, entah apa yang mereka inginkan, mereka tak pernah minta apa-apa dariku, tapi dengan ikhlas dan sabar terus memberi wejangan padaku. Lambat laun membatunya hatiku mulai mencair, melihat kesabaran mereka menuntunku.
Aku tak ingat lagi dengan Bryan. Bahkan aku sudah tak ingat impian-impianku ingin menikah dengan Bryan, juga dengan lelaki manapun. Aku juga lupa menanyakan seandainya bertemu Bryan, apa tujuan ia dulu datang ke pubku, atau mungkin itu hanya halusinasi sosok jelmaan yang akhirnya menuntunku pada kehidupanku yang baru. Aku tak pernah berharap apa-apa selain keluarga dan agama baruku yang mencintai dengan tulus, memberiku kehidupan dan harapan baru untuk sejenak menikmati hidup.
Aku tak ingat, sejak kapan aku masuk islam, mengenakan jubah putih yang mereka sebut mukena. Menyebut asma Alloh yang mereka bilang berdzikir, dan membaca sebuah kitab yang mereka namakan Al Quran. Tapi sejak itu hatiku tenang, aku seperti bayi yang baru terlahir dengan kehidupan yang baru. Baru mengenal Tuhan. Tapi satu yang tak bisa aku sebut pada keluarga baruku, yaitu tentang Maggie. Seorang pelacur kota Paris. Karena di sini aku dipanggil Sarah oleh mereka, aku menyukai nama itu. Aku juga tak menceritakan bahwa HIV dan HPV (human papilloma virus) sudah bersarang di tubuhku sejak 10 tahun yang lalu. Aku tak berani cerita pada bapak, ibu atau Aisyah. Aku takut mereka mengusirku, memperlakukanku seperti orang-orang Sainte-Anne. Aku sangat takut kehilangan mereka. Maaf,, ibu, bapak, Aisyah.
Bertahun-tahun aku tinggal dengan keluarga mereka, dengan sisa uangku, aku mulai mendirikan toko bunga yang sengaja dikelola oleh Aisyah. Berkat ketekunannya, kini toko itu maju pesat, banyak menerima pesanan rangkaian bunga-bunga cantik, bahkan hingga luar kota Bandung. Aku tersenyum bahagia bisa membantu mereka. Seandainya ia tahu dari mana uang yang selama ini aku berikan padanya,, oh tidak. Aku tak berani membayangkannya. Aku terlalu mencintai mereka, keluarga baruku.
Seminggu sekali aku berkunjung dan beristirahat di argapuri mountain resort, di sebuah villa kayu yang nyaman dan sejuk dengan pemandangan yang sangat asri dengan perpaduan gunung dan lembah yang sama-sama hijau disekelilingnya. Aku sengaja membeli villa itu untuk tempat menenangkan diri. Keluargakupun sudah hapal kebiasaanku. Seperti hari ini, sudah seminggu aku tidak turun, menikmati udara pegunungan yang indah.
Tidak, bukan itu, aku terisak, saat ini dadaku semakin sakit, napasku serasa tercekat, nampaknya kanker oropharyngeal yang menggerogoti tenggorokan dan tonsilku semakin mengganas. Tapi aku tak berani cerita pada siapapun selain pada_Nya.
Tuhan,, izinkan sekali saja aku menjadi umatMu, seperti mereka.
*Maggie Kaas yang menjadi Sarah Rahman.
********************************************************
“Aya....!!!”
Buru-buru aku menutup buku itu, buku harian tulisan tangan berwarna merah muda yang sudah lapuk.
“Iya, Mii..!!”
“Kenapa belum tidur, bukannya besok mau ke Jakarta, katanya mau ke perpustakaan nasional”
“Duh, lupa, iya mi, aya lagi nyari data-data buat bahan skripsi dulu”
“Cepet tidur yah, udah malem”
“Iya mi,” aku tersenyum sebelum ibuku menutup pintu kamar.
Ugh, hampir saja ketahuan.
Perlahan aku kembali membolak balik buku kusam itu. Tulisan berbahasa Prancis itu sangat rapi, walaupun banyak huruf-huruf yang mulai hilang terhapus waktu. Sebagai mahasiswi sastra prancis yang sudah hampir skripsi, tentu saja itu tak menjadi kesulitan buatku menterjemahkan kata demi kata yang tertera di situ. Aku menemukan buku serta tulisan-tulisan ini kemarin. Ketika membersihkan villa keluarga yang terletak di gunung argapuri. Aku menemukannya di kotak lemari tante Sarah.
Aku tak mengenal Maggie, aku tak mengenal Sarah apalagi Bryan dan Monicca. Aku hanya sering mendengar ummiku menyebut nama itu. Tante Sarah. Yang menurut ummi adalah saudara perempuannya. Menurut cerita, tante Sarah meninggal karena sakit, ia ditemukan tak bernyawa dalam keadaan tertidur dan masih mengenakan mukena di kamar pribadinya di villa argapuri. Sayang, mereka tak punya fotonya. Yang pasti, setiap minggu, ummi, nenek dan kakek selalu mengunjungi makam yang bernisan “Sarah Rahman”, makam yang di atasnya tumbuh bunga cantik yang harum dan indah. Entah tumbuh karena apa, yang pasti keluargaku tidak menanamnya.
Bimbang, mungkinkah kuceritakan isi tulisan itu pada ibuku.
Astagfirulloh,, sudah jam setengah 12 malam, Aku belum sholat isya...*

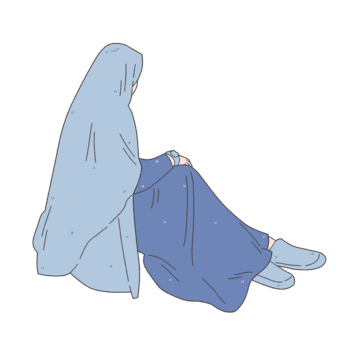









0 Comments
Silahkan tinggalkan pesan di sini: